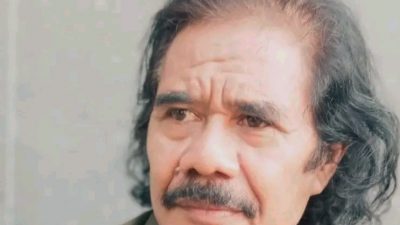“Kalau omong dunia jurnalistik, orang-orang dari kampung yang terjun di dunia tulis-menulis ini saya tak ragu lagi.
Karena kebanyakan dari mereka selain lulusan sekolah unggul, juga dari seminari yang menguasai bahasa Inggris, Jerman, dan Latin serta pengetahuan filsafat dan theologi”
Ansel Deri
DELEGASI.COM – JAKOB OETAMA bukan orang sekampung saya. Pun bukan sekampung bele Marcel Beding, wartawan senior KOMPAS, koran harian paling besar di Indonesia bahkan Asia Tenggara (mungkin bisa diralat kalau saya keseleo lidah).
Satu yang pasti: Jakob Oetama sama-sama wong deso, orang desa. Jakob orang desa dari Jowahan. Desa ini letaknya 500 meter sebelah timur Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi peninggalan jaman purba itu tak pernah pula saya kunjungi selama terjun di dunia jurnalistik. Ibuku, Maria Ose Klobor, yang hampir sebagian besar hidupnya di lereng gunung Labalekan di kampung, malah pernah ke Borobudur.
Tatkala berlibur di Jakarta, ibu diajak saudaranya, Andreas Bera Klobor dan Monce Klobor, putri semata wayang om guru, Pius Klobor dan calon istrinya dari Jogjakarta, Patty Patricia, jalan-jalan ke Jogja. Berwisata.
Ya, ibuku dan om guru Andreas boleh saya sebut sebagai wisatawan domestik. Perjalanan wisata ini di-back up Pius Klobor, putra om guru Andreas Klobor. Pius, selama kuliah di Jakarta, di bawah bimbingan saya di dunia jurnalistik yang mengantarnya eksis di dunia para kuli disket ini.

Meski Jakob dan saya sama-sama dari desa, Jakob miliarder yang punya KOMPAS dan aneka anak usaha di bawah Kelompok Kompas Gramedia (KKG).
Anak usaha KKG menyasar hampir semua kota provinsi di Indonesia. Terutama media cetak dan on-line.
Sedang saya? Saya menduga Jakob tak pernah kenal nama saya. Tapi nama Jakob ada dalam memori saya sebagai anak desa tatkala masuk Kupang tahun 1990.
Jakob lewat KOMPAS bikin saya kaget. Mengapa? Seumur-umur sejak masih kecil di kampung dan masuk Kupang, Timor, tahun 1990, mata saya baru melihat wajah KOMPAS.
Tatkala menginjakkan kaki di Kupang, saya kaget pertama kali melihat ada koran besar bernama KOMPAS.
Di mana? Ya, di kos. Kos Pak Rikardus Daton Klobor dan Pak Jusuf Sesawato Lase, dua dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kos itu sekitaran Jalan Nangka Oebobo.
“Kalau sudah selesai siapkan makan siang untuk bapa bonsu dan Pak Jusuf, kamu gunakan waktu baik-baik untuk baca KOMPAS.
Banyak ilmu dan pengetahuan ada di koran ini. Coba engko liat baik-baik. Di situ macam ada nama orang Lamalera. Namanya, Pak Marcel Beding,” kata Rikar, suatu pagi sebelum ia ke kampus untuk mengajar.
Setelah beres urusan masak dan mencuci baju dan celana kotor, segera bolak balik lembaran koran elite itu dikawal kopi panas & jagung titi dari kampung halaman di Lembata.
Tatkala membaca KOMPAS, nama dalam jajaran staf redaksi seperti Marcel Beding, Pius Karo, dan Ansel da Lopez mulai familiar.
Pak Pius Karo, satu dari dua nama terakhir itu pun belasan tahun baru ketemu dalam sebuah acara keluarga Maumere di Jakarta Timur.
Moat Pius dikenalkan moat Ardi, kerabatnya, setelah tahu saya berhadapan dengan moat Pius, sesama jurnalis dari NTT beda level dan generasi.
“Moat Pius saya suka baca laporannya di KOMPAS kalau ada kunjungan Presiden ke luar negeri. Saya jatuh cinta dengan KOMPAS saat tiba di Kupang.
Saya mulai familiar dengan nama moat, magun Marcel Beding dan om Ansel da Lopez,” kata saya kepada moat Pius Karo.
“Pak Marcel Beding itu wartawan yang sangat brilian. Beliau dari Lamalera, kampung yang sangat terkenal. Orang-orang Lamalera juga pintar-pintar. Mungkin makan ikan segar,” kata moat Pius.

“Bisa saja karena konsumsi ikan segar, tapi lebih dari itu saya lihat banyak orang hebat karena jasa pendidikan Katolik yang menekankan kualitas.
Banyak pula wartawan dari daerah selain lulusan sekolah-sekolah swasta unggul, banyak juga dari sekolah seminari menengah dan tinggi yang sudah mulai menguasai bahasa Inggris, Jerman, dan Latin serta pengetahuan filsafat dan teologi.
Kalau omong dunia jurnalistik, orang-orang dari kampung yang terjun di dunia tulis-menulis ini saya tak ragu lagi. Jadi saya kerap buang badan kalau ditanya apa pernah di seminari.
Jawaban saya, cuma dengar saja cerita emperan seminari; tidak sampe di dalamnya.
Selama di Kupang, saya akrab dengan KOMPAS, selain tentu SUARA PEMBARUAN, JAWA POS, BALI POS, SURYA atau Surabaya Post. Berikut sejumlah majalah besar seperti TEMPO, GATRA, MATRA, TAJUK serta tabloit seperti BOLA, NOVA, DETIK, dan lain-lain.
Mulai tahun 1992, Harian Pos Kupang mulai akrab dengan saya setelah sebelumnya saya hanya puas dengan SKM Dian, milik SVD yang terbit di Ende, Flores. Pun beberapa media lokal yang mulai muncul seiring banyak orang kaya yang terjun dalam bisnis media.
Satu hal yang selalu memacu saya membaca yaitu pengalaman pertama bersua dengan media-media cetak dengan format besar.
Ulasan-ulasan topik lokal para wartawan di koran nasional selalu menggoda. Seorang jurnalis bisa dikenal baik dari gaya menulis berita dan feature yang membuat saya sebagai pembaca seolah hadir atau terlibat dalam peristiwa atau ulasannya.
Ben Oleona, seorang wartawan senior dari Lamalera kerap saya jumpai tulisannya di SURYA menggunakan bahasa Melayu Larantuka atau Kupang.
Asyik membacanya, seolah-olah ia orang Larantuka atau Kupang. Saya pun seumur-umur tak pernah bertemu dengan Ben Oleona.
Kecuali Ambros Oleona, kerabatnya, yang pernah mengajar saya pelajaran Kesenian di SPG Lewoleba awal masuk sekolah calon guru itu tahun 1987.
Bapa guru Ambros pernah melukis seorang pria di papan tulis dan bikin saya terheran-heran. Ia seniman hebat di mata saya yang baru tiba di kota.
Selain nama-nama itu di koran-koran besar terbitan luar NTT, saya juga mulai akrab dengan sejumlah nama lain seperti Damyan Godho, Frans Sarong (KOMPAS), Jack Adam, Adhie Malehere, Cypri Aoer, Chris Mboeik (SUARA PEMBARUAN), Yulius Siyaranamual, Piter A Rohi, Mikael Malimau, Maxi Wolor (SURYA), Bosko Blikololong, Maxi Uun (GATRA), Hilarius Laba Blikololong, dan lain-lain (sekadar menyebut beberapa).
Nama besar yang selalu saya ingat yaitu Gorys Keraf dan Gerson Poyk. Magun Gorys Keraf familiar karena pernah mengasuh rubrik Bahasa di Surya. Sedang Gerson Poyk pernah menerbitkan cerita bersambung Seruling Tulang di Surya. “Seruling Tulang karya bapa Gerson Poyk bagus juga kalau diterbitkan dalam bentuk buku untuk bahan bacaan sekolah-sekolah di NTT.
Beliau itu sastrawan besar yang dimiliki Indonesia yang lahir dari Namodale, kampung kecil di Rote,” kata saya kepada kaka Fanny Jonathan Poyk, putri Gerson, yang juga seorang sastrawati produktif.
Tahun 2011, saya bertemu rekan Cahyo Adji, rekan yang sama-sama ikut merintis OZON. Kami bertemu di Toko Buku Gramedia Matraman Raya, Jakarta Timur. Sebuah buku menaklukkan mata saya.
“Syukur Tiada Akhir: Jejak Langkah 80 Tahun Jakob Oetama.” Judul buku itu lagi ngetren. Harganya terbilang jumbo: sekitar Rp. 80-an ribu. Saya asyik membaca buku dan majalah tak jauh dari Cahyo. Ia menawarkan membeli saya satu eksemplar. Apakah ia tawarkan saya karena pernah singgah di Lamalera, kampung Marcel Beding atau Boto, kampung saya? Saya kira bisa saja. Namun, lebih dari itu ia ingin saya juga tahu sosok Jakob Oetama, orang nomor satu dan owner Kelompok Kompas Gramedia.

Berikut bagaimana lika liku dan perjuangan Jakob dan rekan-rekannya merintis KOMPAS sejak awal hingga eksis menjadi media raksasa nasional dan menjadi bacaan mulai dari masyarakat di kampung-kampung hingga pejabat mulai daerah sampai para menteri dan Presiden RI di Istana Negara.
Satu hal membanggakan, wartawan KOMPAS pernah memotret beberapa orang kampung di tengah jalan usai mereka dari kebun. Kesederhanaan orang-orang kampung yang baru pulang kebun itu rupanya menjadi pemandangan unik di mata jurnalis KOMPAS.
Ia segera mengabadikan momen itu dan muncul di halaman koran itu. Asyik juga.
Tapi siapa sosok Jakob Oetama sesungguhnya? Stanislaus Kostka Sularto atau dalam box redaksi akrab dengan St Sularto, menulis sekilas sosok Jakob.
Jakob lahir di Desa Jowahan, 27 September 1931. Awalnya, Jakob seorang guru. Ia beralih profesi jadi wartawan kemudian mendirikan Harian KOMPAS dan menghandle Kompas Gramedia.
Pernah pula jadi guru SMP Mardiyuwana Cipanas, Jawa Barat tahun 1952 dan SMP Van Lith Jakarta tahun 1953.
Pernah menjadi Redaktur Pelaksana PENABUR di Jakarta tahun 1955. Bersama koleganya, Petrus Kanisius (PK) Ojong mendirikan majalah INTISARI tahun 1963. Kemudian mendirikan KOMPAS tahun 1965.
Dalam merayakan 80 tahun usianya pada 2011, Jakob mengaku tiada kata selain bersyukur tiada akhir.
“Keberhasilan yang dicapai kelompok usaha ini, selain karena kerja keras, sinergi, dan kejujuran dilandasi roh kemanusiaan yang beriman, juga karena semangat mengembangkan penghargaan martabat manusia dan kemanusiaan.
Surat kabar itu harus lebih besar daripada individu-individu serta gabungan individu-individu di dalamnya.
Surat kabar harus lebih arif, lebih adil, lebih bernalar, lebih jujur, lebih peka, dan lebih setia kawan, terutama kepada mereka yang lebih menderita daripada individu-individu maupun wartawan dan karyawannya,” kata Jakob Oetama.
Mungkin resep itulah, sembari berserah kepada Tuhan sebagai orang Katolik, Jakob sukses membawa KOMPAS jadi kompas, penunjuk jalan bagi bangsa dan negara hingga KOMPAS memasuki usia ke-55 tahun 2020.
Terima kasih, Pak Jakob Oetama. Selamat Ulang Tahun ke-55 untuk KOMPAS. Terima kasih para wartawan & karyawan KOMPAS. Salam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
Jakarta, 28 Juni 2020
Penulis adalah
Orang udik penikmat KOMPAS;
Spesial untuk HUT ke-55 KOMPAS
Sumber foto: Fb Dion Db Putra, grup WA Wartawan NTT & Dunia, dan google.co.id