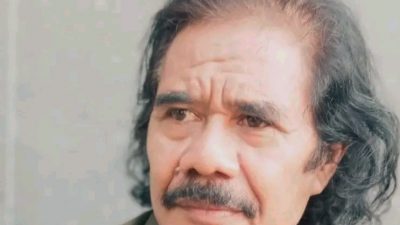Oleh : Dominggus Elcid Li
Seorang Ibu bertanya, “Jika anak bisa belajar di rumah, mengapa para pejabat tidak bisa berpolitik dari rumah, dan malah mengajak warga berkumpul seolah kita sedang berada pada situasi yang biasa-biasa saja dan bukan pandemi? Apakah penyampaian mandat untuk memerintah tidak bisa dilakukan dari rumah, dan tidak perlu berkumpul? Lewat pos misalnya, sehingga orang tidak perlu berkumpul?”
Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini menggelitik. Anak-anak yang bernaung di bawah institusi sekolah saat ini juga sudah teramat bosan tinggal di rumah, tetapi mereka tetap disiplin belajar dengan segala daya upaya. Tak hanya anak yang bosan, orang tua juga sama. Guru pun menanggung beban yang juga tidak mudah.
Sekolah adalah tempat nalar diasah, dan orang diajak untuk berpikir sistematis. Namun, fenomena terbaru yang dipertontonkan para poli-tikus ini seolah hendak mengatakan bahwa cara berpikir sistematis itu hanya untuk diterapkan oleh anak-anak saja, sedangkan para poli-tikus adalah orang dewasa seolah sedang berlatih ‘ilmu kebal’ di lapangan kampanye. Poli-tikus adalah kaum jenis lain yang melampaui segala aturan. Mereka boleh berkumpul, bergerombol, menularkan, dan merasa biasa-biasa saja. Tidak begitu peduli.
Menteri menulis memberikan peringatan para calon kepala daerah ‘yang melanggar protokol kesehatan’. Peringatan ini terlambat. Seharusnya kesalahan mendasar semacam ini sudah harus bisa diantisipasi sejak awal. Kasus positif Covid-19 mulai bermunculan. Telah muncul _cluster ¬_ Pilkada dari calon kepala daerah yang positif terinfeksi pada berbagai tahapan. Andaikan tes massal dilakukan entah berapa lagi yang terinfeksi.
Fenomena ini memperlihatkan hal yang aneh, tetapi dianggap biasa. Para calon kepala daerah bergerak tanpa kontrol. Kondisi ini memperlihatkan kondisi riil. Partai-partai politik saat ini yang tidak lagi mempunyai kemampuan otokritik, sehingga kesalahanan pembuatan kebijakan yang remeh temeh terjadi beruntun, tanpa ada kemampuan membuka jalan sebagai tanda terobosan.
Ada beberapa hal yang membuat partai politik dan para aktornya tidak dapat melihat jauh. ¬_Pertama_ , hampir di setiap tubuh partai politik mengalami monoloyalitas yang akut. Loyalitas tunggal pada pemimpin partai membuat faksi-faksi dalam partai politik hilang. _Kedua_,¬ hilangnya faksi-faksi dalam partai politik juga semakin mengerucut pada persaingan kuasa partai semata dan cenderung buta. Kuasa demi kuasa. Indikator kuasa politik dalam partai bukan lagi soal kemampuan tetapi lebih pada soal siapa.
_Ketiga,_ laboratorium-laboratorium pemikiran tidak tumbuh dalam partai politik. Tidak ada think tank yang bergerak dalam partai politik. Tidak ada simulasi internal yang dikerjakan sebelum kebijakan dikeluarkan. _Keempat,_ situasi ini memperlihatkan ketidakmampuan menentukan prioritas dalam partai politik. Ketiadaan kemampuan menentukan prioritas merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan berpikir strategis.
Partai politik yang bergerak tanpa nalar maupun target terukur merupakan akibat terjauh dari monoloyalitas yang cenderung buta. Jika kondisi ini terjadi pada satu partai semata kita masih bisa mengelak bahwa ini hanya cerita tunggal, tetapi kondisi ini terjadi pada semua partai politik. Tidak ada warna terbosan yang dilakukan oleh satu partai politik pun di Indonesia untuk Covid-19 yang menggambarkan visi brilian partai politik. Sebaliknya, pembedaan ideologis yang ‘seolah-olah ada’ diantara partai politik, tidak menjadi pembeda dalam praktek pembuatan kebijakan.
Munculnya _travel warning_ dari berbagai negara ke Indonesia, bukanlah hal yang dibuat-buat, tetapi mereka mampu melihat sikap masa bodoh para elit Indonesia. Indonesia dianggap tidak berada pada level terbaiknya. Artinya para ‘pemegang tampuk pemerintahan’ Indonesia dianggap tidak menyelesaikan PR-nya dengan baik.
Di tahun 2020 ini kita juga mencatat bahwa pada saat pandemi orang-orang partai bukan bekerja sama mencari jalan keluar, tetapi sibuk dengan agenda pemilihan presiden 2024, dan ancang-ancangnya dimulai dengan Pilkada serentak di berbagai wilayah. Agenda politik politikus itulah yang dianggap riil. Padahal situasi pandemi membutuhkan kecermatan, penguasaan detil, dan intervensi harian yang menyeluruh. Tepat di titik ini kita tidak punya sumber daya tim kerja yang dibutuhkan.
Secara umum pola pengambilan keputusan di aras elit pemerintahan cukup memprihatinkan karena dua hal. _Pertama_, kebijakan yang terlalu didominasi oleh perhitungan-perhitungan ekonomi makro seperti ketakutan terhadap resesi menelantarkan kajian kesehatan masyarakat (_public health_). Sulit kita mendapatkan ada kombinasi kebijakan anggaran yang brilian dari para ekonom sebagai terobosan di era pandemi sebagai buah pemikiran strategi ekonomi-kesehatan di era pandemi. Para ekonom pemerintah juga amat permisif terhadap poli-tikus di panggung kekuasaan. Bisa jadi para ekonom juga tersandera oleh para poli-tikus. Namun pola menjaga keseimbangan anggaran negara tanpa ada terobosan juga hanya menunda kematian. Ya, seandainya uang pilkada bisa diberikan untuk bikin laboratorium tes massal. Entah kenapa inovasi murah semacam ini tidak tiba di tangan para ekonom negara?
_Kedua_, partai politik sebagai pemegang kendali rotasi kekuasaan pun tidak terkontrol dan tidak bergerak dalam kemampuan nalar maksimal. Para elit partai politik bergerak dalam asumsi kelompok yang cenderung homogen. Ke-serupa-an yang menjadi-jadi baik di dalam partai maupun antar partai hanya melahirkan situasi katak dalam tempurung. Tidak ada terobosan.
Kebijakan yang disodorkan pun memunggungi realitas. Sebelum memasuki era _New Normal_, mereka sibuk bikin kebijakan _rapid test._ Setelah _New Normal_ terbukti ‘Tidak Normal’, malah membuat kita semakin terkunci, jargon yang dibawa adalah ‘vaksin sudah siap diberikan’.
Komunikasi politik yang dijalankan tidak didasarkan pada realitas terkini. Artinya dengan sekian infrastruktur kepartaian yang begitu dahsyat, kemampuan untuk mengintegrasikan masukan real time dari para konstituen tidak terjadi. Orang tahu bahwa untuk menuju pada penemuan vaksin butuh waktu, dan butuh usaha. Sebelum vaksin ditemukan harus ada disiplin yang memadai untuk mengontrol angka penyebaran. Tepat di sini para poli-tikus menolak untuk disiplin dalam cara berpikir sistematis.
Bahkan di era _New Normal_, komando pemberian informasi Covid-19 ditutup. Katanya agar orang tidak panik. Kebijakan yang keliru mulai dipanen dampaknya. Relaksasi yang dipaksakan berimbas pada melemahnya kewaspadaan, dan melonjaknya angka penderita dan kematian.
Jika hari-hari ini ada ide untuk mempekerjakan preman untuk mengawasi orang di pasar agar tertib menggunakan masker, maka ide ini seharusnya digunakan untuk para elit juga. Seandainya ada yang mengawasi agar mereka tertib berpikir, tentu kita bisa mencapai sesuatu. Tetapi mekanisme kritis semacam itu ditutup total, sehingga kita seolah tidak punya jalan keluar.
Jika hari-hari ini grafik krisis mengalami _rebound_, grafik yang menderita infeksi bukannya menurun tapi menunjukkan _trend_ naik dan di ambang tidak terkendali maka kita sedang dihukum karena kesalahan sendiri. Hal yang paling ironis dalam situasi ini adalah upaya melakukan demokratisasi sejak tahun 1998 kembali pada titik anarki. Kondisi para pemegang kekuasaan yang tidak mampu melihat cahaya juga tidak mampu memberikan cahaya untuk warga negara.
Jika hari-hari ini kata-kata para pemimpin tidak berarti di tengah publik, ini terjadi bukan karena orang membangkang, namun orang tidak melihat apa yang diucapkan oleh pejabat yang bersangkutan menjadi bagian dari dirinya. Para pejabat seakan ada di ‘dunia lain’. Fantasi-fantasi berlipat yang memunggungi kenyataan terjadi di seluruh sektor. Selama kenyataan tidak dilihat, dipelajari, dan dikerjakan,tidak ada jalan keluar. Kita hanya bisa berjanji ‘vaksin akan tiba’. Entah itu kapan? Jika itu masih bersifat ‘entah kapan’, mengapa tidak kerjakan sesuatu yang riil? Inilah situasi anarki yang terselubung.
Penulis adalah Peneliti dan Moderator Forum Academia NTT